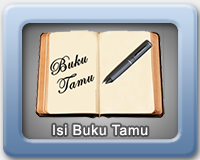| Makalah Komisi - C - (#19) |
|
KHOTBAH DI GEREJA KATOLIK: MEDIA PEWARISAN KEUTAMAAN DAN Abstrak Gereja Katolik diperkenalkan di Indonesia oleh pedagang Portugis dan Belanda. Sebagai agama misioner, misi Gereja dikembangkan melalui berbagai pendekatan. Satu di antaranya pendekatan kultural yang dipraktikkan oleh Pastor Van Lith (1863-1926) dengan memanfaatkan bahasa dan budaya Jawa untuk memperkenalkan ajaran Kristiani. Hal tersebut tampak pada film dokumenter Betlehem van Jawa yang menunjukkan upaya Van Lith mempelajari seni dan budaya Jawa, seperti bermain gamelan, menyaksikan pertunjukan wayang kulit, dan menerjemahkan doa dan buku pelajaran agama Katolik dari bahasa Latin ke bahasa Jawa. Penggunaan bahasa pribumi dalam upacara keagamaan tersebut dilegitimasi pusat Gereja Katolik Roma dalam Dokumen Konsili Vatikan II (1962-1965) mengenai Konstitusi “Sacrosanctum Concilium” tentang Liturgi Suci. Ihwal penggunaan bahasa pribumi dikemukakan pada artikel 36 yang melegitimasi penggunaan bahasa pribumi untuk kepentingan ibadat. Salah satu bagian ibadat yang berisi pengajaran adalah “Liturgi Sabda” berupa pembacaan kitab suci, kemudian diikuti khotbah oleh pastor yang memimpin ibadat. Tulisan ini akan mengkaji penggunaan bahasa dalam khotbah di Gereja Katolik. Kajian dilakukan secara holistik dengan melihat faktor objektif bahasa khotbah dan nilai yang disemaikan melalui khotbah, faktor genetik menelusuri latar belakang penggunaan bahasa dan isi yang disampaikan oleh pengkhotbah, dan faktor afektif dengan menelusuri tanggapan jemaat sebagai pendengar. Sumber data diambil dari empat gereja, yaitu dua gereja di Kabupaten Bantul (Ganjuran dan Klodran) dan dua gereja di Kabupaten Sleman (Banteng dan Pakem) Keempat gereja tersebut setiap minggu masih menyelenggarakan satu kali ekaristi berbahasa Jawa. A. Pendahuluan Ketika berlangsung peringatan wafatnya Pastor Tan Soe Ie, SJ., tanggal 26 Februari 2010, salah satu kesaksian keluarga mengatakan hal berikut. “Jika akan berada di lingkungan atau daerah baru belajarlah bahasa. Penguasaan bahasa yang baik memungkinkan bisa menyelami kehidupan masyarakat penuturnya. Bahasa juga berpotensi untuk dapat berbagi duka, berbagi suka, berbagi pengalaman, berbagi perasaan, dan untuk mengungkapkan hal-hal yang emotif dan mendasar.” Ajakan tersebut dibuktikannya ketika bertugas di Timor Timur beliau menguasai bahasa Tetun dengan baik. Oleh karena itu, beliau dapat sangat akrab dengan masyarakat Timor Timur ketika itu. Pada akhir masa hidupnya beliau tinggal di Dusun Ponggol, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, sebuah dusun di kaki Gunung Merapi sisi selatan. Di tengah masyarakat penutur bahasa Jawa, beliau juga sangat fasih berbahasa Jawa. Oleh karena itu, beliau mudah mengajak para petani untuk membuat inovasi dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan, dan penggunaan pestisida yang sebagian besar diupayakan secara organik. Pada anak-anak, pemerolehan dan pemelajaran bahasa memiliki kemungkinan dari berbagai jalur, seperti jalur agama (khotbah, upacara ritual, nyanyian pujian, dan bahan-bahan bacaan) dan seni pertunjukan yang menggunakan medium bahasa. Dengan demikian, penggunaan bahasa Jawa untuk kegiatan keagamaan memberi sumbangan terhadap penguatan pemerolehan dan pemelajaran bahasa Jawa terutama bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan dan upacara keagamaan. Upacara ritual keagamaan merupakan salah satu forum penggunaan bahasa yang bergengsi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Jawa dalam upacara ritual tersebut meningkatkan gengsi bahasa Jawa yang memberi penguatan penggunaan bahasa Jawa di masyarakat. Isi khotbah merupakan media pewarisan keutamaan yang lazimnya disesuaikan dengan tema ibadat yang sudah dirancang untuk peribadatan selama satu tahun. Kajian ini dilakukan secara holistik dengan memperhitungkan faktor objektif, genetik, dan afektif. Faktor objektif berupa ujaran verbal bahasa Jawa yang digunakan pengkhotbah dalam upacara Ekaristi di Gereja pada hari Sabtu atau Minggu. Faktor genetik berupa pandangan pengkhotbah mengenai latar belakang penggunaan bahasa Jawa yang digunakan dalam khotbah dalam Ekaristi yang diperoleh melalui wawancara. Faktor afektif adalah tanggapan jemaat yang mendengarkan khotbah yang diperoleh melalui wawancara. Penetapan penelitian secara holistik ini diharapkan memberi gambaran yang lebih utuh mengenai potensi khotbah sebagai sarana konservasi bahasa Jawa. B. Bahasa Ragam Keagamaan Penggunaan bahasa dalam bidang keagamaan dapat dikategorikan sebagai salah satu penggunaan bahasa untuk keperluan khusus. Gläser menyebutnya sebagai language for specific purposes (1998:469). Dalam bahasa Indonesia model penggunaan secara khusus tersebut disebut ragam bahasa. Dalam politik bahasa nasional dikatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai
1. lambang kebanggaan nasional, 2. lambang identitas nasional, 3. alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar 4. alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagaibahasa resmi negara,
1. bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan,bahasa 2. Poerwadarminta (1967:16) membedakan bahasa bergaya menjadi a. ragam jurnalistik, b. ragam ilmiah, dan
Dasar penamaan ragam tersebut cenderung karena lingkungan penggunaan dan bukan karena karakteristik bahasanya yang khusus.
1. daerah, 2. pendidikan, dan 3. sikap penutur.
Ragam bahasa menurut jenis pemakainya dapat dirinci menjadi
1. ragam dari sudut pandangan bidang atau pokok persoalan, 2. ragam menurut sarananya, dan 3. ragam yang mengalami percampuran.
Sudaryanto (1997:50-1) membagi ragam bahasa menjadi lima, yaitu
1. ragam literer, 2. ragam akademik, 3. ragam filosofik, 4. ragam bisnis, dan 5. ragam jurnalistik.
1. globalisasi, 2. kebijakan bahasa dan pendidikan, 3. kebijakan pemerintah, 4. sikap penutur bahasa, 5. sumber daya manusia, 6. agama, 7. aksara, dan 8. dukungan dana (2010:19-20).
Ihwal agama sebagai penyebab keterancaman dan kepunahan dikatakan oleh Saragih sebagai berikut.
1. Penggunaan bahasa Latin hendaknya dipertahankan dalam ritus-ritus
Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya
Ing Ratri
Di Waktu Malam
1. kebijakan bahasa dan pendidikan, 2. kebijakan pemerintah, 3. sikap penutur bahasa, 4. sumber daya manusia, 5. agama, 6. aksara, dan 7. dukungan dana (2010:19-20).
Ihwal agama sebagai penyebab keterancaman dan kepunahan dikatakan oleh Saragih sebagai berikut.
1. Greja ingkang leres inggih menika ingkang dipun degaken kados 2. Paraban langkung misuwur tinimbang naminipun. Parto Cethit, 3. Greja kita mila nggadhahi kekirangan. ‘gereja kita memang memiliki
2 Klodran, Bantul
1. Mangga kita mbudidaya dados tiyang ingkang beja amargi leres lan 2. Slamet, beja durung mesti apik lan bener.
3 Widyoraharjo, MSF. Banteng, Sleman
1. Sabda rahayu mboten ingkang kita pikiraken. Mboten ingkang badhé 2. Sabda rahayu ingkang kita lampahi. Dados nyoto ingkang kita
4 Bagus Irawan, MSF. Banteng Sleman
1. Pamartobat, kanggo nyawisaké Natal. ‘pertobatan untuk menyiapkan 2. Para Romo ing Sleman padha rawuh ing wilayah-wilayah, supaya 3. Ora perlu wedi dosané mengko diéling-éling karo ramané. Para
5 Pepeng, MSF Banteng Sleman
1. Mbirat pepeteng supados ngraosaken pepadhang Dalem Gusti. 2. Pawartos dalem Gusti kanggé manggihaken margi ingkang padhang.
6 Saji, PR Pakem, Sleman
1. Bapak ibu temtu gadhah pengalaman ingkang mboten saget dipun 2. Kula péngin dados Katolik SD kelas gangsal, anggènipun baptis 3. Sing penting, dadi Katolik ora merga wong tuwa nanging saka atiné
Enam data yang tersaji di atas menunjukkan dominasi nilai religius. Data 1 menunjukkan kepada umat mengenai dasar pembentukan Gereja. Hal tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan Gereja yang dituangkan dalam Penanggalan Liturgi. Khotbah sekaligus mengajak umat untuk setia kepada Gereja yang didirikan oleh Yesus seperti yang disabdakan Yesus dalam Injilnya, yaitu Gusti Yesus ngedegaken grejanipun wonten ing karang padhas. ‘Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di atas karang padas.’ Hal tersebut bersifat eksklusif seperti halnya pada data 4 yang berisi ajakan untuk melakukan pertobatan dalam menyambut Hari Raya Natal. Para gembala umat secara bergilir melayani Sakramen Pengampunan Dosa kepada umat dengan mendatangi paroki-paroki yang ada di wilayah Sleman. Data 5 berisi ajakan untuk menyingkirkan kegelapan dan berusaha menemukan jalan terang yang memungkinkan orang melakukan kebaikan. Data 6 menekankan bahwa semangat menjadi Katolik jangan karena ajakan, bujukan, atau menuruti keinginan orang lain, akan tetapi karena pilihan dan keputusan pribadi.
1. Ragam Krama
4 Bagus Irawan, MSF. Banteng Sleman 1. Ragam Krama
6 Saji, PR Pakem, Sleman 1. Ragam Krama
1. Kowe iku petrus lan ana ing karang padhas iki anggonku arep 6. Rumiyin wonten romo menjadi kopasus komandan para suster. 7. Rumiyin wonten ugi zaman abad pertengahan menika malah
Data di atas menunjukkan bahwa alih kode dari ragam krama ke ngoko terjadi pada saat menyampaikan kutipan bacaan seperti pada data (1)1. Data (1)2 menunjukkan alih kode sebagian, dari Jawa ke Indonesia, sedangkan (1)3 menunjukkan alih kode keseluruhan yang cenderung digunakan untuk memberikan penekanan agar dapat diterima seluruh umat. Hal yang sama tampak pada data (1)4 dan (1)5. Data (1)6 dan (1)7 alih kode terjadi untuk menjelaskan istilah (akronim) yang berisi gejala yang terjadi secara eksklusif di lingkungan gereja. Tipe alih kode selanjutnya masih seperti gejala di atas, seperti tampak pada data berikut.
1 Ganjuran
2 Bantul
3 Banteng
4 Pakem 1. Persiapan menggunakan bahasa Indonesia.
♦ Anasom. 2006. “Perkembangan Bahasa Jawa dalam Tradisi ♦ Basuki, Widodo. 2004. Medhitasi Alang Alang: Kumpulan ♦ Gläser, R. 1998. “Language for Specific Purposes”. Concise ♦ Halim, Amran (Editor). 1984. Politik Bahasa Nasional 2. Jakarta: ♦ Soenarja, A., SJ. (Penerjemah). 1996. Kitab Suci. Yogyakarta: ♦ Kompas. 2009. 26 Desember. “Peringatan Natal: Konservasi Budaya LAI. 1976. Alkitab. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. ♦ Macaryus, Sudartomo. 2010. “Konservasi Bahasa Melalui Kegiatan ♦ Macaryus, Sudartomo. 2011. “Pengembangan Bahasa Jawa: Sebuah ♦ Macaryus, Sudartomo. 2011. “Teks Liturgi: Media Konservasi ♦ McCormick, K.M. 1998. “Code-switching and Mixing”, Concise ♦ Moeliono, Anton M. Dkk. (Penyunting). 1988. Tata Bahasa Baku Obor. 1993. Dokumen Konsili Vatikan II. Terjemahan R. ♦ Poedjosoedarmo, Soepomo. 1978. “Kode dan Alih Kode”, dalam ♦ Poerwadarminta, W.J.S. 1967. Bahasa Indonesia untuk Karang ♦ Saragih, Amrin. 2010. “Revitalisasi Bahasa Daerah dalam Konteks ♦ Sudaryanto dan Sulistiyo (ed). 1997. Ragam Bahasa Jurnalistik dan
|