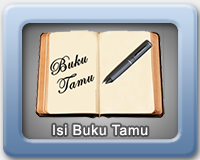| Makalah Komisi - C - (#22) |
|
Model Sikap Jawa terhadap Ideologi Asing Abstrak
1. Hanya masuk ibadah atau menyusun kekuatan politik? 2. Jika Ibadah, haruslah Sultan Pengging menghadap karena tunduk 3. Jika tidak menghadap, Sunan Kudus menyatakan bahwa itu berarti
Pada akhir cerita, Mataram memiliki musuh orang-orang dari Surabaya dan gagal menaklukannya (Sudibjo, 1980; h. 221).
1. Pembunuhan terhadap Ki Ageng Pengging, putra dari pejabat 2. Sunan Kudus menyuruh Arya Peanngsang membunuh Sunan Prawata.
Kegagalan itu karena Sultan Pajang mampu membaca kelicikan yang dijalankan oleh Arya Penangsang dan Sunan Kudus. Pertemuan yang dijadikan sebagai media penjebak Sultan Pajang ternyata gagal mencapai target.
1. Menetapkan visi untuk keputusan-keputusan strategis dalam sebuah 2. Meminta perlindungan kepada penguasa. Permintaan itu pada saat kelompok muslim mendapatkan perlindungan d di tanah Ampel, 3. Menghimpun kekuatan. Ketika pemerintah memberikan legalitas 4. Mengancurkan kekuatan lama secara fisik dan non-fisik. Ketika Perihal kenyataan itu, sebab utamanya adalah prasangka yang baik setiap kedatangan orang asing. Karena itu, pengarang menilai:
1. Perihal visi kelompok minoritas, pengarang Jawa melihat visi itu 2. Perihal perlindungan kaum mioritas adalah bukti kebaikan, tetapi 3. Perihal penggalangan massa, sikap Jawa memperlihatkan bahwa itu 4. Tanggapan terhadap penghancuran ideologi lama, pengarang
Sikap di atas secara tegas dijelaskan dalam kutipan berikut ini:
1. Karakter bangsa merupakan gambaran luaran yang ditopang oleh 2. BTJ menjabarkan sikap yang terbuka terhadap ideologi asing karena 3. Darmagandhul berpijak pada sikap tertutup terhadap ideologi asing 4. Baik BTJ maupun Darmagandhul memiliki pendapat yang sama Fenomena aktual yang terjadi pada masa sekarang ini adalah
• Ideologi kebangsaan mestinya dikembangkan dari nilai-nilai lokal • Pemerintah mestinya menjalankan kebijakan strategis yang berbasis • Visi kesejahteraan mestinya diarahkan pada kedaulatan di bidang • Pada masa depan kiranya diperlukan kajian terhadap nilai-nilai lokal Universitas Negeri Jakarta, 1 Oktober 2011 Lampiran Sekuen Dua Cerita A. Sekuen Babad Tanah Jawi
1. Konflik Raja Gilingwesi yang telah menikahi ibunya, Dewi Sinta 2. Hubungan raja-raja Majapahit dengan para tokoh Islam di Demak 3. Cerita Jaka Tarub yang berhasil menikahi Retno Nawangsih karena 4. Pengaruh Sunan Giri yang mulai melemahkan Majapahit dengan cara 5. Strategi Sunan Kudus mendirikan Kesultanan Demak dan Pajang 9. Pemberontakan Untung Suropati yang diantisipasi VOC dengan cara 10. Keputusan Pangeran Puger untuk bekerja sama dengan Belanda 12. Penolakan Mataram terhadap penagihan oleh VOC akibat 14. Konflik antara Pangeran Puger dan Amangkurat (350- 360). 15. Perkembangan kota Semarang yang dibangun oleh VOC sehingga 16. Perjalanan Amangkurat meminta bantuan ke sejumlah tempat 20. Pengangkatan pemimpin pasukan di Kartasura oleh VOC
Catatan: Penulisan nama dan istilah dalam sekuen itu berdasarkan pada naskah transliterasi huruf Latin dan translasi Bahasa Indonesia Babad Tanah Jawi.
1. Pupuh 1: Percakapan antara Kiai Kalamwadi dengan tokoh 9. Pupuh 9: Tiga analisis kehancuran Majapahit, yakni kekejian 10. Pupuh 10: Penjelasan tentang ajaran Jawa Buddha yang sudah
Catatan: Penulisan angka dalam kurung setelah keterangan sekuen adalah halaman awal dan halaman akhir.
♦ Ali, As'ad Said. 2009. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan ♦ Arikunto, Suharsimi. 1999. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ♦ Berg, C. C. 1938. “Javaansche Geschiedschrijving”. s’Graven ♦ ______.1955. “Twee nieuwe publicaties betreffende de ♦ _____. 1957, “Babad en Babadstudie”, Indonesie'X, 's-Hage. ♦ Brandes, J. L. A. 1920, Pararaton (Ken Arok) of het Boek der ♦ _______. 1904. Nagarakretagama, Lofdicht van Prapanjtja op koning ♦ Ciccarely, Saundra K dan Glenn E. Meyer. 2006. Psychology. New ♦ Cruse, D.A. 1986. Lexical Semantics. Great Britain: Athenoeum ♦ Djajadiningrat, Hoesein. 1913. Critische Beschouwing van de ♦ Graaf, H.J.de dan T.H. Pigeaud. 2001. Kerajaan Islam Pertama di ♦ ________. 2004. Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI. ♦ Hofstede, G. 2001. Culture Consequences: Comparing Values ♦ Kanazawa, Satoshi. 2007. “The Evolutionary Psychological Evolutionary, and Cultural Psychology (2007). ♦ Kawuryan, Magendra W. 2006. Tata Pemerintahan Negara ♦ Klann, Gene. 2007. Building Character. San Fransisco: John Willey ♦ Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya 1-3. Bogor: ♦ Mai, R. & A. Akerson. 2003. The Leader as Communicator: Creativity. New York: American Management Association. ♦ Mardiwarsito, L. 1985. Kamus Jawa Kuna Indonesia. Ende Flores: ♦ Moedjianto. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh ♦ Moleong, Lexy. J. 1989. Metode Penelitian Kwalitatif. Jakarta: ♦ Mulyono, Slamet. 2008. Kamus Pepak Basa Jawa. Jakarta: Buku ♦ Nazir, Zulhasril. 2007. Kuasa dan Harta Keluarga Cendana. Jakarta: ♦ Paul, Richard W. dan L Elder. 2002. Critical Thinking: Tools for ♦ Perlovsky, L.I. 2010. "Mind mechanisms: concepts, emotions, ♦ __________. 2007. Modeling Field Theory of Higher Cognitive ♦ Purwadi. 2007a. Babad Tanah Jawi: Menelusuri Jejak Konflik. ♦ Purwadi. 2007b. Sejarah Raja-raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu. ♦ Ras, J. J. 1968. Hikajat Bandjar; A Study in Malay Historiography. ♦ ______. 1987. “The genesis of the Babad Tanah Jawi; Origin and ♦ Robson, Stuart. 1995. Desa Warnnana (Nagara Krtagama By Mpu ♦ Rele, Vasant G. 1927. Bhagawad-Gita: An Exposition on the Basis ♦ Ricklefs. M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah ♦ Ryle, Gilbert. 1999. Concept of Mind. Great Britain: William ♦ Saleh, Ismail. 2001. Proses Peradilan Soeharto Presiden RI ke 2. ♦ Shashangka, Damar (penerjemah). 2011. Darmagandhul: Kisah ♦ Shanahan, M.P. 2005. "Consciousness, Emotion, and Imagination: A AISB 2005 Symposium on Next Generation Approaches to Machine ♦ Slametmulyana. 1979. Negara Kretagama dan Tafsir Sejarahnya. ♦ ____________. 2005a. Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah ♦ ____________. 2005b. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan T ♦ Soekarno. 1964. Di Bawah Bendera Revolusi (jilid I dan II). ♦ Soetrisno, Slamet. 2006. Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah. ♦ Sudibjo. 1980. Babad Tanah Jawi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. ♦ Suhandana, K. M. 2008. Nagara Krtagama & Pararaton: Sejarah ♦ Sumarsono, H. R. 2008. Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam ♦ Sriwibawa, Sugiarta. 1977. Babad Tanah Jawa. Jakarta: PT. Dunia ♦ Suripan, Sadi Hutomo. 1981. Penelitian Bahasa dan Sastra Babad ♦ Suta, I Putu Gede. 2010. “Role of Intelligence in Leadership ♦ Tedjoworo, H. 2001. Imaji dan Imajinasi: Suatu Telaah Filsafat ♦ Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta. 2001. Kamus Basa Jawa ♦ Wijana, I Made. 1977. De Nagarakrtagama I, Turunan H Kern. ♦ Wilkins, D.A. 1972. Linguistic in Language Teaching. Great Britain: ♦ Winter, C. F. 1948. Javaansche Zamenspraken. Amsterdam: Martinus ♦ Yamin, H Muhammad. 1962. Tatanegara Majapahit. Jakarta: Yayasan ♦ Yatman, Darmanto. 1985. “Ilmu Jiwa Kramadangsa: satu Usaha ♦ Yusuf, Suhendra. 1994. Pengetahuan ke Arah Pendekatan Linguistik.
♦ Anak Bajang Menggiring Angin and Hikayat Sri Rama” (1999). ♦ Promoter of the thesis is Prof. Dr. Th Sri Rahayu Prihatmi, MA.
♦ Introduction to Study of Postcolonial Indonesia ♦ Principles of Basic Indonesian Language.
♦ The Achievements of Paper Competitions ♦ The Achievements of Fiction Writing Competition Grant of Novel |