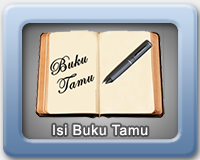| Makalah Komisi - C - (#29) |
|
Bahasa dan Sastra Jawa dalam Tradisi Pesantren Abstraksi Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional di Nusantara. Keberadaan pesantren di Nuasantara telah mengakar kuat dengan sosio-kultural dan ruh keislaman masyarakat. Kondisi itulah membuat pesantren menjadi berkarakter lokal (baca: indegenous). Maka, benar pernyataan Wahid yang menyebut pesantren sebagai sebuah subkultur. Sejak awal berkembang sampai dengan saat ini, pesantren masih tetap menggunakan dan memertahankan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar dan bahasa komunikasi dalam pergaulan. Penggunaan bahasa Jawa dalam tradisi pesantren itu disebut bahasa Jawa Kitabi. Bahasa Jawa di pesantren digunakan untuk menginterpretasikan kitab-kitab kuning. Selain itu, bahasa Jawa di pondok pesantren juga digunakan untuk menulis karya sastra. Tradisi bersastra di lingkungan pesantren masih terbatas pada tradisi sastra kitab atau sastra ajaran. Makalah ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik sekaligus fungsi bahasa dan sastra Jawa dalam pesantren. Karakteristik-karakteristik yang ditemukan antara lain, bahasa Jawa (pegon) digunakan untuk menerjemahan bahasa Arab, bahasa Jawa-Kitabi yang digunakan untuk menerjemahkan kitab lama tidak mengenal tingkatan, dan sastra Jawa dalam pesantren kebanyakan berupa nazaman. Sementara itu, bahasa dan sastra Jawa dalam tradisi pesantren di samping memunyai fungsi pendidikan, pengajaran, dan spiritual, juga memunyai fungsi perekat kebersamaan. Karakteristik tersebut akan tetap menjadi basis identitas pesantren dan tentunya akan bermanfaat bagi pembangunan budaya nasional yang dalam konteks global dapat dijadikan sebagai sumber kearifan dalam kehidupan berbangsa. Kata kunci: bahasa, sastra Jawa, tradisi pesantren, Jawa Kitabi 1. Pendahuluan Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua produk budaya Indonesia. Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk di negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berakar di negeri ini, pondok pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan sejarah bangsa. Pondok pesantren memiliki kultur khas yang berbeda dengan budaya sekitarnya. Kekhasan ini ditunjukkan dengan tradisi yang bersifat turun-temurun, misalnya tradisi sistem belajar mengajar secara bandongan dan sorogan. Bandongan adalah suatu metode pengajaran dengan cara guru/kiai membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa Arab (baca: kitab kuning) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sedangkan para santri mendengarkan sambil memberi catatan pada halaman-halaman kitab yang sedang dibaca. Metode sorogan adalah para santri membaca kitab, sementara kiai atau ustaz menyimak sambil mengoreksi atau mengevaluasi bacaan seorang santri satu persatu (ada yang dilakukan bersama-sama) (Haedari, 2006:26); (Dhofier, 1984:28—29); (Qomar, 2002:142—143). Penggunaan bahasa Jawa di lingkungan pesantren terkait dengan proses keberlangsungan belajar mengajar di pesantren (Damami dalam Sedyawati, 2001:112). Damami menggarisbawahi bahwa penggunaan bahasa Jawa hanya terjadi pada pesantren yang menggunakan pendidikan belajar mengajar dengan menggunakan metode bandongan dan sorogan, tidak terjadi pada pesantren yang mengunakan bahasa pengantar bahasa Arab dengan selingan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut pengkajian karakteristik dan fungsi bahasa serta sastra Jawa di pondok pesantren merupakan langkah yang cukup penting. Mengingat bahwa pondok pesantren, khususnya di Jawa memunyai sejarah perjalanan panjang yang membuatnya menjadi berkarakter. Penulisan ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan karakteristik dan fungsi bahasa dan sastra Jawa di pondok pesantren. 2. Pesantren, Bahasa Jawa, dan Identitas Nasional Para ahli sepakat bahwa abad ke 15, daerah pesisir utara Jawa seperti, Tuban, Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menjadi basis utama penyebaran agama Islam di Jawa. Di tempat-tempat itu, para mubalig sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa harus merangkak dari lapisan bawah dan menyebar melalui masyarakat pedesaan sepanjang pesisir. Di sepanjang masyarakat pesisir mereka mendapatkan sambutan yang hangat bahkan dipandang sebagai rahmat untuk keluar dari kegelapan. Di daerah-daerah itu, mereka bersama masyarakat mendirikan basis-basis penting berupa pusat-pusat religi yang cukup kuat dan strategis. Basis-basis yang menjadi pusat semacam ini sekarang dikenal dengan nama pondok pesantren (Pegeaud dalam Purnomo, 2002:10). Proses penyebaran Islam di daerah pesisir yang diikuti mengalirnya kepustakaan agama melahirkan lingkungan tradisi baru yang dinamakan budaya pesantren, yang mau tidak mau merupakan tradisi agung kedua yang mengimbangi tradisi agung di lingkungan istana (Simuh, 1999:18). Dari sinilah kemudian lahir peradaban baru di Jawa, yaitu 1. aksara pesantren Jawa, yang disebut Pegon, 2. bahasa Jawa Islam, yang disebut sebagai bahasa Jawa-Kitabi, dan 3. teks-teks keagamaan Islam atau kesusasteraan Islam yang disebut
Keadaan seperti itu pesantren disebut oleh wahid dengan istilah subkultur. Interpretasi ini tidaklah bertentangan dengan fakta bahwa pesantren adalah sebagai subbudaya. Mengingat pesantren memunyai sistem nilai yang merupakan bagian dari masyarakat luas.
♦ Abdullah, Muhammad. 2008. Aspek Eskatologi Naskah Syi’ir ♦ Al-Hamidy, Abu Dzarrin dkk. 2008. Sarung dan Demokrasi: Dari ♦ Ali, Moch. 2006. Pengajaran dan Pendidikan dalam Kultur Pesantren ♦ Anasom. 2006. Perkembangan Bahasa Jawa dalam Tradisi ♦ Dhofier, Zamakhsari. 1984. Tradisi Pesantren: Studi tentang ♦ Haedari, Amin. 2006. Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek ♦ Hamdany. tt. Nail Al-Aswaq: Tarjamah Taisir Al-Khalaq fi Al-Ilmi ♦ Imron, Zawawi. 1998. Muara Sastra Pesantren. Sastra Dan Budaya ♦ Mansur, Tholhah Ibnu. tt. Pantun Nasehat, Pantun Asmara, Syair- ♦ Muzakka, Muh. 2006. ”Puisi Jawa Sebagai Media Pembelajaran ♦ Purnnama, Bambang, dkk. 2002. Kesastraan Jawa Pesisiran: Sebagai ♦ Qomar, Mujamil. 2002. Pesantren: Dari Tranformasi Metodologi ♦ Sayuti, Suminto A. 2007. ”Bahasa, Identitas, dan Kearifan Lokal ♦ Sedyawati, Edi, dkk. Sastra Jawa: Suatu Tinjauan Umum. Jakarta: ♦ Simuh. 1999. Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik ♦ Teeuw, A. 1984. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. |