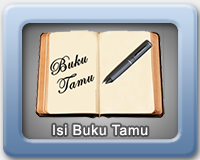| Makalah Komisi - C - (#41) |
|
Fenomena Bahasa Tegal Dalam Tingkah Laku Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tersebut dapat mempermudah setiap orang dalam berinteraksi terhadap sesama. Bahasa sebagai alat komunikasi, adalah bahasa yang digunakan sebagai alat berinteraksi (menjalin sebuah komunikasi) atau hubungan antara dua manusia atau lebih, sehingga pesan yang dikmaksudkan dapat dimengerti. bahasa juga sebagai alat beradaptasi, bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi dan interaksi sehari-hari dapat sebagai sarana beradaptasi. Sebagai contoh saat berada di suatu daerah yang baru dikenal, kita dapat menggunakan bahasa daerah setempat sebagai alat berinteraksi terhadap lingkungan dan masyarakat untuk belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Saat menjalin komunikasi dengan sesama tentu saja kita membutuhkan sesuatu yang bisa membuat lawan bicara memahami maksud yang akan disampaikan, maka kita perlu bahasa ungkap (lisan) adalah bahasa mempunyai fungsi ekspresif, dimaksudkan untuk mampu menggungkapkan atau menggambarkan sebuah maksud ,gagasan dan juga perasaan. Selain ada bahasa ungkap (lisan), tentu saja kita juga memerlukan bahsa tulis dimaksudkan sebagai alat pengatur atau pengontrol terhadap sesuatu. Bahasa tulis juga penting untuk terus mengontrol keberadaan bahasa, seperti dalam laporan UNESCO dalam penelitiannya tentang eksistensi bahasa ibu (daerah) dewasa ini dalam setiap tahun lebih dari 5 bahasa ibu punah. Hal ini dikarenakan bahasa tulis tak berjalan dalam komunitas masyarakat. bahasa sebagai media aktualisasi sikap memegang peranan penting dalam membentuk karakter diri. Tingkah laku memang erat dengan bahasa. Ungkapan budi bahasa dan tutur kata selalu mengacu pada tingkah laku, tabiat, budi pekerti akhlak dsb. Oleh karena itu tingkah laku tergambar dalam budi bahasa,ditengah kerumunan budaya global yang saling bersaing untuk memikat manusia, terkadang manusia kehilangan jati diri, hilangnya jati diri tersebut mengakibatkan karakter diri lemah, karakter yang melemah membawa pengaruh yang negative diantaranya berkurangnya ketegasan diri. Akibatnya masyarakat kita cenderung mudah marah, tidak sopan, brutal sehingga menjadi cerminan masyarakat yang berbudaya tidak tampak dalam perilaku dan tutur kata. Diera global dewasa ini, dimana jarak dan waktu hanyalah merupakan sekat tipis menjadikan perikehidupan masyarakat kuat saling mempengaruhi. Kondisi yang demikian menjadikan tak satupun bahasa-bahasa didunia mampu survive bertahan hidup tanpa pengaruh bahasa lain, bahkan terdapat beberapa bahasa ibu (daerah) tak mampu hidup, akhirnya punah tergilas derap perkembangan dan kemajuan peradaban. Maka agenda Kongres Bahasa Jawa sangatlah penting untuk tetap menjaga eksistensi bahasa jawa sebagai akar kultur jawa, jati diri etnik jawa, lambang kebanggan daerah dan sarana pergaulan dalam keluarga dan masyarakat. Biro Pusat Statistik (1983) menyebutkan bahasa jawa masih dipakai oleh sebagian terbesar masyarakat Indonesia yaitu sebanyak 59,4 juta, bahasa sunda 22,1 juta, bahasa madura 6,2 juta dan minang 3,5 juta. Perdana menteri Singapura Lee Kwan Yew pernah menciptakan kampanye penggunaan bahasa Mandarin untuk mengurangi penggunaan bahasa Inggris melalui Bulan Mandarin setiap tahun di bulan Oktober sejak th 1979. imperialisme budaya yang menyusup di negara-negara berkembang menciptakan semua serba barat. Meskipun bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional di Indonesia disahkan pada 28 oktober 1928, yaitu bertepatan pada saat sumpah pemuda. Dalam segi bahasa nasional berfungsi sebagai Lambang identitas nasional, lambing kebanggan kebangsaan, sebagai alat pemersatu komunikasi dan juga pemersatu sebagai bangsa yang multi suku, ras, agama pun tak bisa lepas dari pengaruh budaya imperialisme. Sikap westernisasi ini di respon dengan upaya melestarikan identitas masyarakat masing-masing daerah baik berupa kebudayaan, bahasa maupun rasial. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam usaha melestaraikan bahasa jawa tetap harus memperoleh perhatian bersamaan dengan kepedulian kita terhadap bahasa nasional Indonesia. Bahasa Jawa mempunyai beberapa dialek, yang bisa dibedakan dari ciri-ciri tertentu. Sepintas perbedaan itu dapat dilihat dari ucapan dan kosakatanya. Namun, dua hal itu belum mewakili ciri perbedaan secara keseluruhan sebelum dikaitkan dengan pembicaraan struktur dialeknya. “Bahasa jawa mempunyai 4 dialek dan 13 subdialek. dialek-dialek itu adalah: Banyumas, Pesisir Utara, Surakarta dan Jawa Timur. Adapun subdialek-subdialek itu meliputi : Purwokerto, Kebumen, Pemalang, Banten Utara, Tegal, Semarang, Rembang, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Surabaya dan Banyuwangi.” (Uhlenbeck, 1972:75) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta tahun 1981 pernah menerbitkan hasil penelitian Suwadji, Slamet Riyadi, Dirgo Sabariyanto, dan Gina. Mereka itu meneliti Struktur Dialek Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Tengah (Tegal dan sekitarnya). Mereka mengakui hal itu bukan penelitian pertama mengingat pada tahun 1903, AHJG Walbeehn, sarjana berkebangsaan Belanda meneliti hal serupa, Het Dialect van Tegal (Dialek Tegal). Dialek Tegal merupakan salah satu kekayaan bahasa Jawa. Meskipun memiliki kosakata yang relatif sama dengan bahasa Banyumas, pengguna dialek Tegal tidak serta-merta mau disebut kelompok ngapak, karena beberapa alasan antara lain perbedaan intonasi, pengucapan dan makna kata. Pertama kali mendengar bahwa bahasa tegal sebagai bahasa ngapak-ngapak, pada tahun 80 an banyak mahasiswa Tegal yang kuliah di Jogja, Solo dan Semarang sering mengeluh dengan adanya sebutan sebagai mahasiswa ngapak-ngapak. Sehingga sampai sekarang dialek Tegal dianggap masuk dalam bagian bahasa ngapak-ngapak yang secara umum dianggap bahasa kasar serta dipertautkan dengan kelas ’’rendah’’, bahasa kaum proletar. Bagaimana pun keberadaan bawasa Jawa dialek Tegal maupun Banyumas tetap harus diakui, dihormati dan dikembangkan, oleh karena dialek itu adalah ragam bahasa yang secara nyata hidup dan menjadi alat komunikasi efektif didalam kehidupan bermasyarakat masing-masing. Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1811 pernah melakukan penelitian di Jawa, yang ditulisnya dalam buku The History of Java. Dalam buku tersebut Raffles menulis antara lain, yang membedakan dialek Tegal dengan dialek bahasa Jawa lainnya, bahasa Jawa Tegal diucapkan dengan cara memanjangkan (bunyi) vokal, misalnya,’’Nang keeeene, kyehhh ( disini, nih). Entah siapa yang memulai setiap kali bicara bahasa Tegal selalu diidentikkan dengan bahasa ngapak-ngapak. Padahal dalam kosakata dialek Tegal tidak ditemui kata ngapak, atau yang mirip. Pada dialek Banyumas kata ngapak tidak memiliki arti ’’jelas’’, hanya diambil dari dialek yang mewakili ciri-ciri Banyumas, ’’Ora ngapa-ngapa’’ (tidak apa apa). Orang Banyumas mengucapkannya, ’’Ora ngapak-ngapak’’. Barangkali dari sinilah istilah ’’ngapak-ngapak’’ muncul. Sedangkan orang Tegal mengucapkannya, ’’Ora papa’’ atau ’’ora apa-apa.’’ Tegal adalah salah satu kota yang terletak di pesisir utara pulau jawa, kota kecil hanya memiliki 4 (empat) kecamatan. Tetapi menjadi sebuah kota yang memiliki mobilitas tinggi, bukan saja di sektor perekonominya, tetepi juga disektor lainnya. Hal ini disebabkan Tegal sebagai kota lintas Jakarta - Surabaya, juga sebagai jalur lintas selatan (Tegal-Purwokerto). Dengan letak kota yang dipertigaan wilayah, bukan saja sebagai kota lintas, tetapi juga sebagai kota transit. Sehingga memungkinkan selalu terjadinya interaksi berbagai orang dari berbagai daerah, memungkinkan juga masuknya pengaruh bahasa (dialek). Bahasa Tegal dipakai bukan saja oleh warga Tegal, tetapi dipakai juga oleh masyarakat Brebes bagian timur, sedangkan Brebes bagian barat dipengaruhi bahasa Sunda (Cirebon) dan bagian selatan dipengaruhi Banyumas, seperti didaerah kecamatan Bumiayu sampai pada perbatasan wilayah Banyumas. Bahasa Tegal juga dipakai di Slawi (kab Tegal) dan sebagian masyarakat Pemalang bagian barat. Sebagai warga dari sebuah kota lintas sekaligus kota transit, orang Tegal tak mudah terpengaruh dengan orang-orang pendatang, terutama dengan bahasanya. Namun orang Tegal sangat mudah untuk meniru (menyesuikan diri) dalam pemakaian bahasa dari daerah lain, bagi pendatang sangat sulit untuk cepat menguasai bahasa (dialek) Tegal. Sehingga dalam hal ini, setiap orang (yang bukan orang Tegal) memakai bahasa Tegal dianggapnya lucu, padahal hakekatnya bukan sebuah hal yang lucu, tetapi dibalik sebagai bahan melucu tersembunyi hal kekaguman bagi yang (dianggap) berhasil menirukan bahasa Tegal. Memang tidak dipungkiri, bahwa sebagian besar menganggap bahwa bahasa Tegal menjadi (sebagai) bahasa lawakan. Hal tersebut bisa dimaklumi karena bahasa Tegal lebih pada ekspresinya, sehingga bila diucapkan oleh orang yang bukan orang Tegal berkesan lucu. Angger wong wis nyekel ekspresine bahasa Tegal, nganggo bahasa apa bae ya krasa ekspresif. Bahasa Cina, Arab, Inggris, utawa bahasa Indonesia dewek - Puisi Lisan Tegalan, Dalsikum - karya Eko Tunas. ( kalau orang sudah memegang (memahami) ekspresinya bahasa Tegal, memakai bahasa apa saja ya terasa ekspresinya. Bahasa Cina, Arab, Inggris atau bahasa Indonesia sendiri - Puisi Lisan Tegalan. Dalsikum - karya Eko Tunas). Berangkat dari ketidakpahaman pada ekspresi bahasa Tegal, para pelawak memanfaatkannya sebagai bahan lawakan. Seperti Cici Tegal yang bukan orang Tegal, Parto Patrio, sesekali Warkop juga memakai dan masih banyak lagi deretan artis yang memakai bahasa Tegal sebagai bahan lawakan. Dampak dari itu semua ada beberapa orang yang merasa minder dengan bahasa Tegal, seperti terjadi pada seorang figuran disebuah sinetron misteri pada tahun 96, bahkan ada beberapa public figure yang juga mempunyai perasaan yang sama. Padahal sebagai bahasa, bahasa Tegal yang sebagian orang menyebut sebagai bahasa Jawa dialek Tegal, sebagaimana bahasa daerah lain juga merupakan bahasa yang "serius". Ia merupakan pencerminan karakter orang Tegal dan sekitarnya yang juga berkecenderungan serius. Sementara itu ada juga penilaian tentang bahasa Tegal sebagai bahasa jawa kasar, padahal dalam bahasa Tegalpun ada tatanan bahasa halus. Seperti “kwe badogen sisan ben wadukmu njeblug” (itu makan sekalian agar perutmu meledak) ini kalimat bahasa tegal yang kasar, sedangkan “kwe panganen sisan ben wareg” (itu makanlah sekalian supaya kenyang) ini kalimat bahasa Tegal halus. Bahasa Tegal juga bisa lebih ekpresif, mari kita baca salah satu puisi.
1. Pola pembentukan bahasa gaul Tegal menggunakan distribusi fonem. 2. Pola pembentukan bahasa gaul Tegal dengan suku kata yang dibalik.
Kata prokem sendiri merupakan bahasa pergaulan kalangan tertentu agar dalam berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Agar kalimat mereka tidak diketahui oleh kebanyakan orang, mereka merancang kata-kata baru dengan cara yang dikehendai/disepakati. Masing-masing komunitas (daerah) memiliki rumusan sendiri-sendiri. Pada dasarnya bahasa ini untuk memberikan kode kepada lawan bicara. Belakangan ini bahasa prokem mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa pergaulan anak-anak remaja. Dalam konteks kekinian, bahasa pergaulan anak-anak remaja ini merupakan dialek bahasa non-formal yang terutama digunakan disuatu daerah atau komunitas tertentu. (*) |